

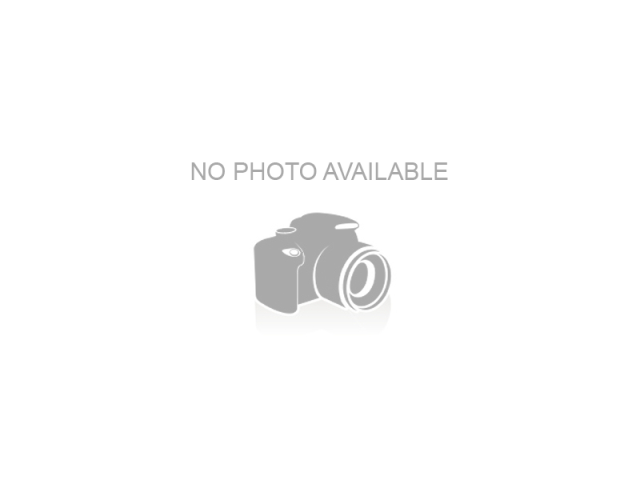
Carito Luhak Nan Bungsu- Sangat menarik Pemerintah Nagari Ampalu, Kerapatan Adat Nagari dan Badan Permusywaratan Nagari bersama Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI mengajukan sebuah naskan hasil penilitian yang berjudul : EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT NAGARI AMPALU DAN KETERGANTUNGANNYA DENGAN HUTAN oleh TIM : Welly Febriari, S,Si,. Roky Septriani, SH. Asrusl Aziz Sigalingging,SH. Yudi Fernandes,SH. Ryan Thanoesya,S.Pd, Leni Permata Sari, SH. Depitriyadi, S.IP dan Ahmad Salim Ridwan, S.Si.
Dalam saran penelitian mereka disebutkan, perlu dilakukan duduk bersama atau dengar pendapat antara Masyarakat Adat Ampalu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengakomodir eksistensi Masyarakat Adat Ampalu dalam sebuah Produk Hukum Daerah dalam hal ini Peraturan daerah dan turunannya agar menjadi Masyarakat Hukum Adat yang sah dimata hukum positif.
Sebagai Kabag Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota hal ini sangat menarik bagi saya pribadi, pasalnya di Sumatera Barat belum ada Nagari mempunyai keberanian untuk membuat terobosan hal seperti ini yang dasar hukumnya jelas ada.
Dasar hukum dapat kita baca menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa : “Ketentuan Umum Angka 1 UU Desa (UU No.6/2014) menggatakan : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja nama lain ini Nagari di Sumatera Barat.
Sejak dulu, Sumatera Barat atau Minangkabau hanya mengenal nama Nagari tidak ada Nagari Adat. Cuma dalam menyikapi terhadap UU No 6 ini, Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan umum angka 1 di atas harus kembali kepada hak asal usul/ atau hak tradisional, sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 18 jika kita ingin mengembalikan hak hutan oleh masyarakat adat yang telah diambil oleh berbagai perusahaan yang dalam perjanjiannya ada sampai 50 tahun mungkin tak lama lagi habis masa perjanjiannya, kemungkinan di Sumatera Barat hampir 35.000 ha hutan rakyat yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan swasta atau pemerintah.
Hal ini dapat kembali kepada masyarakat adat dengan mempedomani PUTUSAN Nomor 35/PUU-X/2012 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tapanuli, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu di Kampar dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Banten.
Dalam perdebatan-perdebatan tentang masyarakat adat dalam konteks Negara yang sedang dibangun pada masa-masa awal kemerdekaan telah mendapatkan porsi yang besar dalam sidang-sidang BPUPKI, yang kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) dikemukakan bahwa: ?dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa” . Selanjutnya disebutkan bahwa ?Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerahtersebut?;
Dengan penjelasan itu, para pendiri bangsa hendak mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah ’susunan asli’ tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau Zelfbesturende landschappen atau kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang lingkungan (landscape) yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat, yang dapat dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah Zelfbesturende dan landschappen. Artinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah wilayah.
Hendak pula dikatakan bahwa penyelenggaraan Negara melalui pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan apalagi sengaja dihapuskan oleh Pemerintah; Secara sosiologis, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif dengan hutan. Di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan hutan tercermin dalam model-model pengelolaan masyarakat adat atas hutan yang pada umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya berisi aturan mengenai tatacara pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, perburuan satwa dan pemungutan
hasil hutan.
Hal usul nagari apabila kita melihat catatan lama sebelum kemerdekaan tahun 1945 dipimpin oleh Kerapan Nagari, kerapan nagari ini adalah wakil rakyat dari unsur (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda). Anggota Kerapan Nagari dipilih oleh Unsur : niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai inilah yang disebut kepemimpinan tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Nagari dipimpin oleh Penghulu Pucuak yang disebut Pangupalo (Penghulu Kepala).
Percepatan Pengakuan Hutan Adat
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012, yang menyebutkan, hutan adat bukan lagi bagian hutan negara, KLHK—dulu Kementerian Kehutanan—menerbitkan pengganti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak, dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P21 tertanggal 29 April 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
Pasal 4 aturan itu, membagi status hutan jadi tiga ketegori, yakni, hutan negara, hutan adat dan hutan hak. Aturan sebelumnya, sama dengan UU 41/1999, membagi status hutan dalam dua kategori, yaitu, hutan negara dan hutan hak. Selain substansi itu, peraturan pengganti ini mengatur tentang peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat tahap pertama.
Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK P.21/2019 ini bertujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat dan mememperbaiki ketentuan Permen LHK Nomor P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak .
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 29 April 2019. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak mulai berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta.
Berbagai jenis pengertian hutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah:
a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
b. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
c. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
d. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
e. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
f. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
g. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
h. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Masyarakat hukum adat dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Kehadiran Permen LHK P.21 diharapkan dapat mendorong dan mempercepat penetapan hutan adat. Namun ekspektasi melalui regulasi seperti ini tidak cukup. Sebagaimana pengalaman dan pembelajaran sebelumnya, hambatan struktural, pendanaan dan kapasitas, masih dijadikan kendala.
Hambatan lain dan sangat berarti adalah berhubungan dengan persyaratan penetapan hutan adat, yang masih dipertahankan Permen LHK P.21 pada Pasal 5, bahwa penetapan hutan adat dilakukan melalui permohonan pemangku adat kepada Menteri. Permohonan harus memenuhi syarat :
1. Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
b. terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
1. Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau
2. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
c. terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
d. dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
e. adanya Surat Pernyataan yang memuat:
1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
2. persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.
3. Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
4. Format Surat Permohonan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Proses legislasi untuk menghasilkan Perda dan substansi pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah dan hutan adat, cukup rumit, memerlukan waktu lama dan dana besar. Masih terdapat perbedaan persepsi tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, terjadi perdebatan definisi subjek masyarakat adat dengan keragamannya dan belum kunjung berakhir, tanpa kejelasan kepastian dipenuhinya hak hukum masyarakat adat.
Apakah daerah mempunyai kemampuan untuk mengikuti proses politik legisliasi, serta ongkosnya mahal. Setiap peraturan daerah tentang penetapan Perda memerlukan biaya Rp. 500 juta sampai Rp. 2 miliar, termasuk untuk konsultasi dan biaya pembuatan peta tersebut.
Kita menunggu Kebijakan selanjutnya.
Saiful Guci , 28 Juli 2020
Feedback